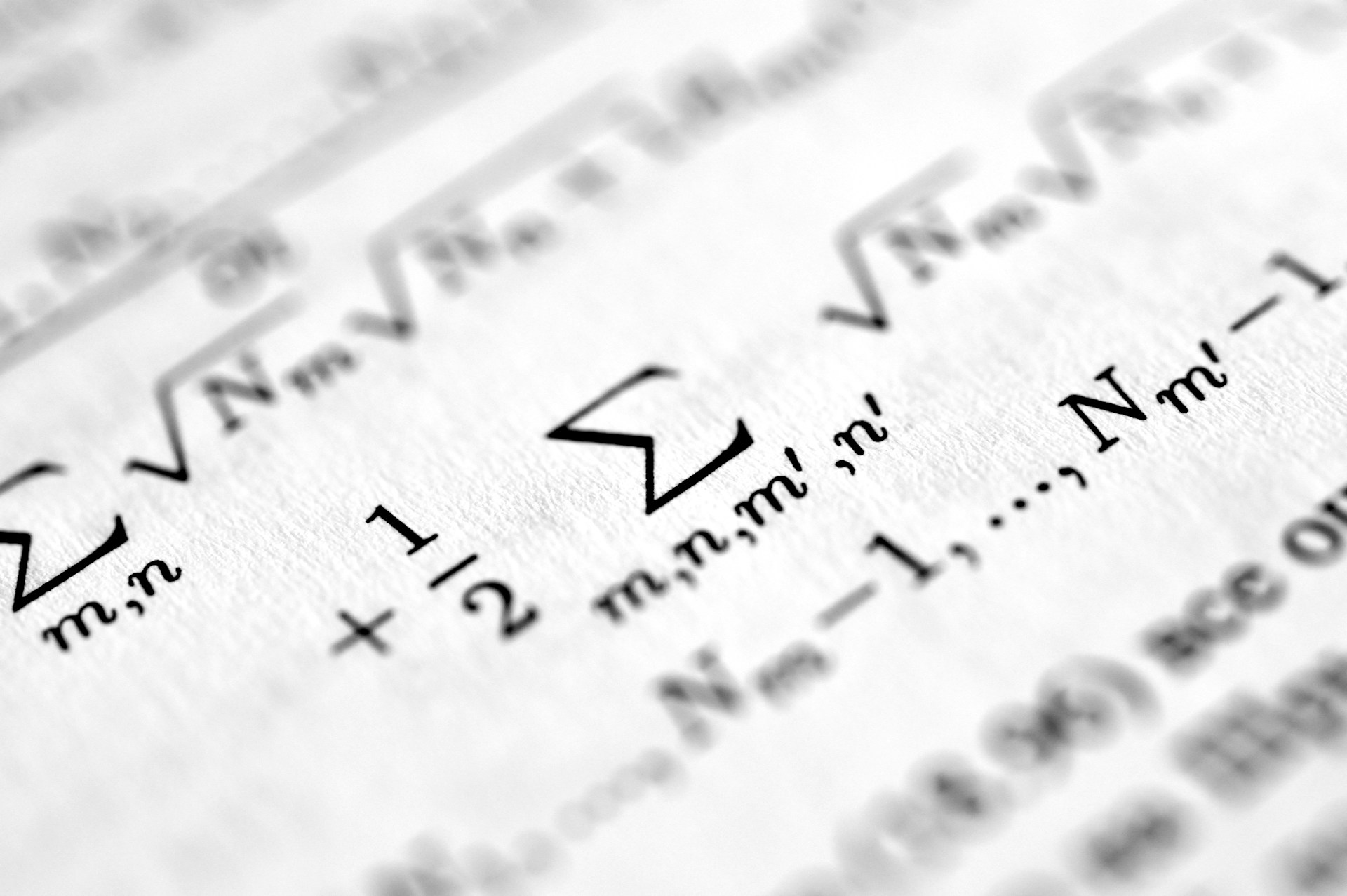Era AI di Sekolah: Panduan bagi Orang Tua dan Strategi Pendidik Menghadapi Krisis Berpikir Kritis
Memasuki tahun ajaran baru, pemandangan yang semakin umum di sekolah-sekolah adalah lembar persetujuan yang harus ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Namun, mulai tahun ajaran 2025–2026, ada klausul baru yang menonjol: persetujuan atas “penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab”. Dari pembelajaran imersif hingga tutor yang dipersonalisasi, AI kini telah merambah ke setiap sudut dunia pendidikan. Namun, implementasinya masih sangat bervariasi, menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan orang tua dan pendidik.
Kesenjangan Literasi AI dan Peran Penting Orang Tua
Kebijakan mengenai AI yang dibuat secara tergesa-gesa sering kali hanya menekankan pada integritas dan kepatuhan, sementara detail teknisnya diserahkan kepada masing-masing guru. Di satu sisi, para ahli memperingatkan bahwa AI berisiko merusak keterampilan berpikir kritis. Di sisi lain, orang tua khawatir akan adanya kesenjangan literasi AI yang semakin lebar antara siswa yang cepat beradaptasi dan para guru yang mungkin tertinggal.
“Anak-anak melesat jauh dalam pemahaman teknologi ini, sementara sekolah-sekolah masih berusaha mengejar ketertinggalan,” kata Victor R. Lee, seorang afiliasi fakultas di Stanford HAI yang memimpin program AI+Education di Stanford Accelerator for Learning. “Sangat penting bagi orang tua untuk mendukung anak-anak mereka dan ikut serta dalam membentuk kebijakan yang sedang berkembang ini.”
Lee menawarkan tiga langkah yang dapat diambil orang tua agar tetap terinformasi dan terlibat aktif.
1. Cari Tahu Bagaimana Guru Menggunakan AI Sebelum mengambil sikap, orang tua perlu memahami bagaimana guru di sekolah anak mereka berencana memanfaatkan teknologi AI. Informasi ini bisa didapatkan dari situs web sekolah, silabus mata pelajaran, atau melalui percakapan langsung dengan guru. Berbagai platform pendidikan seperti Duolingo dan Khan Academy telah meluncurkan tutor berbasis AI untuk membantu siswa belajar bahasa asing dan matematika melalui percakapan interaktif. Perusahaan seperti Kahoot juga menggunakan AI untuk menciptakan permainan edukatif yang dipersonalisasi. Orang tua perlu mengetahui apakah alat-alat ini didukung dan dianjurkan di sekolah anak mereka.
Di luar alat yang disetujui sekolah, siswa secara mandiri menggunakan model bahasa seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk riset, menyusun draf, dan merevisi tulisan. Beberapa sekolah merespons dengan perangkat lunak pendeteksi AI, yang sayangnya terbukti tidak konsisten dan terkadang salah menuduh siswa melakukan plagiarisme padahal mereka menyerahkan karya orisinal. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa pendidik mulai beralih ke sumber daya seperti inisiatif CRAFT, sebuah program AI yang dirancang bersama oleh akademisi Stanford dan guru sekolah menengah untuk membantu siswa memahami dan mempertanyakan output AI.
2. Terlibat dengan Pimpinan Sekolah Bagi orang tua yang memiliki kekhawatiran, Lee menyarankan untuk berdialog langsung dengan administrator sekolah. Lima pertanyaan ini dapat menjadi panduan untuk memulai percakapan:
-
Apakah sekolah memiliki kebijakan AI untuk tahun ajaran ini? Jika ya, di mana kami bisa melihatnya?
-
Alat AI spesifik apa yang disetujui atau dilarang di kelas?
-
Bagaimana sekolah mendukung para guru dalam mempelajari strategi dan sumber daya pendidikan AI yang baru?
-
Pesan apa yang ingin sekolah sampaikan kepada siswa tentang AI, yang dapat kami perkuat di rumah?
-
Apakah sekolah memiliki komite AI yang bisa diikuti oleh orang tua untuk berbagi ide dan rekomendasi?
3. Berdiskusi dengan Anak tentang AI Saat ini masih terlalu dini untuk menilai dampak perkembangan AI secara akurat. Namun, yang terpenting adalah membuka jalur komunikasi. Orang tua perlu berbicara dengan anak-anak mereka tentang aturan dan etika penggunaan AI, baik yang ditetapkan oleh sekolah maupun keluarga.
Tantangan di Perguruan Tinggi: Mahasiswa ‘Mengalihdayakan’ Pikiran
Kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga menjadi isu besar di tingkat perguruan tinggi. Para profesor di berbagai kampus kini menghadapi kepanikan baru: ketakutan bahwa mahasiswa membiarkan ChatGPT dan alat AI generatif lainnya mengambil alih proses berpikir mereka.
Namun, seorang peneliti pendidikan berpendapat bahwa krisis sebenarnya bukanlah kecurangan, melainkan sistem pendidikan tinggi yang terus menguji keterampilan yang justru paling dikuasai oleh AI, sambil mengabaikan kemampuan unik manusia.
Dalam esainya untuk The Conversation, Anitia Lubbe, seorang profesor di North-West University, Afrika Selatan, menyatakan bahwa universitas terlalu “fokus pada pengawasan” penggunaan AI daripada mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah mahasiswa benar-benar belajar? Menurutnya, sebagian besar penilaian masih menghargai hafalan dan pembelajaran mekanis, “tugas-tugas yang justru paling baik dilakukan oleh AI.”
Lubbe memperingatkan bahwa jika universitas tidak memikirkan kembali cara mereka mengajar dan menilai, mereka berisiko menghasilkan lulusan yang mahir menggunakan AI tetapi tidak mampu mengkritik hasilnya. “Keterampilan mengevaluasi dan menganalisis teks buatan AI sangat penting untuk berpikir kritis,” tulisnya.
Lima Strategi Pendidik untuk Melawan Ketergantungan pada AI
Alih-alih melarang AI, Lubbe menyarankan agar universitas memanfaatkannya untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dilakukan mesin: refleksi, penilaian, dan penalaran etis. Ia mengusulkan lima cara bagi para pendidik untuk melawan fenomena “mengalihdayakan pikiran”:
-
Ajarkan Evaluasi Output AI sebagai Keterampilan. Profesor harus meminta mahasiswa untuk menginterogasi hasil dari alat AI generatif—mengidentifikasi di mana jawaban yang dihasilkan tidak akurat, bias, atau dangkal sebelum menggunakannya dalam pekerjaan mereka.
-
Rancang Tugas Secara Bertahap. Daripada membiarkan AI menangani seluruh proyek, dosen harus merancang tugas yang membimbing mahasiswa melalui tingkat pemikiran yang semakin dalam—dari pemahaman dasar, analisis, hingga penciptaan orisinal.
-
Promosikan Penggunaan AI yang Etis dan Transparan. Mahasiswa harus memahami bahwa penggunaan yang bertanggung jawab dimulai dengan keterbukaan—menjelaskan kapan, bagaimana, dan mengapa mereka menggunakan alat seperti ChatGPT.
-
Dorong Tinjauan Sejawat (Peer Review) pada Karya yang Dibantu AI. Ketika mahasiswa saling mengkritik draf yang dihasilkan dengan bantuan AI, mereka belajar mengevaluasi teknologi sekaligus pemikiran manusia di baliknya.
-
Hargai Refleksi, Bukan Hanya Hasil Akhir. Penilaian harus mempertimbangkan bagaimana mahasiswa menggunakan AI—apakah mereka mendokumentasikan prosesnya, membenarkan pilihan mereka, atau menunjukkan pembelajaran melalui perbandingan dengan penalaran mesin.
Peringatan Lubbe digaungkan oleh para pendidik lainnya. Kimberley Hardcastle, seorang profesor bisnis di Northumbria University, menulis bahwa AI memungkinkan mahasiswa untuk “menghasilkan karya canggih tanpa melalui perjalanan kognitif yang seharusnya diperlukan,” dan menyebutnya sebagai “revolusi intelektual” yang berisiko menyerahkan kendali pengetahuan kepada perusahaan teknologi raksasa. Kekhawatiran utamanya adalah AI secara perlahan menggerus kemampuan berpikir kritis yang menjadi fondasi utama pendidikan.